Oleh : Miftahul Alim (Ketua LTN-NU Bontang)
Berbicara tentang kopi dan ngopi saat ini tengah menjadi sesuatu yang berbeda. Walaupun sebenarnya "ngopi" itu sendiri diambil dari kata dasar kopi. "Ngopi" bisa juga disebut sebagai aktifitas atau aksi langsung dalam menginterpretasikan cara menikmati seduhan kopi. Hanya saja karena perkembangan bahasa, kini "ngopi" mengalami pergeseran makna. Saat ini kata "ngopi" tidak melulu harus menunjukkan arti sebuah aktifitas menikmati racikan ataupun seduhan kopi. Tidak sekali atau dua kali saat ketika saya mengajak teman untuk "ngopi" dia malah pesan es teh.
Dari warung kopi ini, biasanya para penikmat kopi akan memulai dialog. Kadar atau bobot yang dibahas tergantung pada komunitas mereka. Dari pembahasan yang remeh, sampai dengan pembahasan yang ruwet. Begitulah warung kopi. Tempat idaman bagi para pencari jati diri.
Dari tempat ini kita bisa membuka cakrawala berpikir. Ide-ide yang tidak terduga sebelumnya tak jarang lahir dari warung kopi. Walaupun hal ini bukan pola pasti, tapi dapat dipastikan bahwa banyak ide atau gagasan besar justru lahir dari tempat yang tidak perlu biaya besar untuk mengunjunginya. Karena tak jarang orang ke warung kopi, hanya pesan 1 cangkir kopi dengan tarif lima ribu tapi menghabiskan waktu berjam jam disana.
Bicara tentang terorisme dan radikalisme. Kebanyak mereka yang sudah terkena virus ini, mereka memiliki patrun berpikir eksklusif dan satu arah. Hal inilah menjadi sebab pemahaman dalam agamanya menjadi timpang atau tidak berimbang.
Kondisi seperti ini memang sudah dikondisikan oleh para pendoktrinnya. Agar mereka hanya menerima satu paham saja tanpa mengkomparasikan dengan paham atau ajaran-ajaran lain. Itulah sebab paham ekstrimis yang dimiliki seseorang semakin hari menjadi semakin kuat. Tak heran jika suatu saat mereka siap kapan saja dengan suka rela menjadi "pengantin" (dalam bahasa mereka) untuk melakukan aksi bunuh diri. Interaksi mereka hanya menerima saja, tidak ada memberi. Dan memang tak ada ruang untuk memberi.
Berbeda dengan interaksi di warung kopi. Lebih eksklusif dan terbuka. Siapa pun boleh menerima atau pun memberi, pendapat se ekstrim atau se keras apapun boleh dilontarkan. Biasanya pendapat pendapat yang seperti ini akan lunak dengan sendirinya mencair mengikuti suasana. Tidak ada yang mendominasi. Semua diberikan waktu dan ruang yang sama untuk bersuara.
Dari warung kopi kita belajar menerima perbedaan. Bukan hanya sekedar menerima perbedaan ras, suku, agama ataupun budaya, tapi juga kompleksitas pemikiran. Membuka cara pandang, cara berpikir dan cara mendengar. Agar kita dapat memahami manusia seutuhnya. Hal inilah yang tidak dimiliki oleh mereka kaum ekstrimis. Mereka hanya mau apa yang mereka ingin dipahami oleh orang lain. Mereka tidak mau berusaha memahami orang lain. Sampailah pada fase jika pemahaman dari mereka tidak diterima, maka jalan kekerasanlah yang menjadi solusi bagi mereka. Tidak ada dialog, tawar menawar, tidak ada toleransi.
Orang yang banyak aktifitasnya diwarung kopi, setidaknya mereka sudah belajar memahami orang lain. Yang tidak dimiliki oleh para ekstrimis itu. Andai saja para ekstrimis itu mau duduk dan dialog tentang apa yang mereka inginkan, tentu akan ada titik terang untuk menjawab problema yang ada dibeban mereka. Bukan justru menutup diri dari publik dan bersikap ingklusif. Inilah awal mula penyakit ekstrimisme dan radikalisme akan menjangkit kepada seseorang.
Ayo duduk, ngobrol, diskusi dan ngopi. Ingsya Allah semua masalah dapat dipecahkan. "Bagaimana kalau tidak juga menemukan solusi ?", Kalau tidak ada solusi. Ya ditinggal ngopi lagi. Gitu saja kog repot. 😊
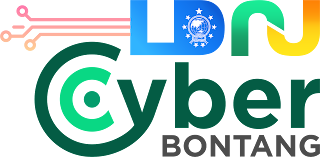


Posting Komentar