FIKIH GUS DUR
Penerapan Fikih Jinayah
Oleh: Hikmat Abdurochman, M.Pd
A. Pengertian Fikih Jinayah
Fikih jinayah
terdiri dari dua suku kata, yaitu fikih dan jinayah pengertian fikih secara
bahasa berasal dari lafal fagiha, yafqahu fiqhan, yang berarti mengerti,
paham. Pengertian fikih secara istilah yang di kemukakan oleh Abdul Wahab
Khallaf bahwa fikih adalah ilmu tentang hukum-hukum syara’
praktis yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci. fikih adalah himpunan hokum-hukum
syara’
yang bersifat praktis yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci.[1]
Jinayah menurut bahasa adalah nama
bagi hasil perbuatan seseorang yang buruk dan apa yang diusahakan. Sedangkan
menurut istilah adalah suatu istilah untuk perbuatan yang dilarang oleh syara’
baik perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta, atau lainnya.
Fikih Jinayah adalah mengetahui berbagai ketentuan hukum tentang
perbuatan-perbuatan kriminal yang dilakukan orang-orang mukallaf, sebagai hasil
pemahaman atas dalil-dalil yang terinci yang mengganggu ketentraman umum serta
tindakan melawan perundang-undangan.[2]
B. Penerapan Fikih Jinayah
Fikih jinayah pada dasarnya bertujuan untuk
melindungi lima hal: Agama, jiwa dan harga diri, keturunan, akal, dan harta (Maqashidus
syari’ah). Fikih Jinayah
sebagian sudah diatur dalam Al-Quran seperti larangan zina, menuduh zina,
makar, mencuri, qisas dan lainnya yang bertujuan untuk melindungi manusia atas
hak-haknya (Daf’ul mafsadah).[3]
Dalam penerapannya, hukum fikih
jinayah walaupun aturannya sudah terperinci dalam Al-Quran selain hukum ta’zir,
belum seluruhnya dilaksanakan dalam kehidupan umat Islam. Bahkan di Indonesia,
penerapa fikih jinayah sangat sedikit dilakukan karena terdapat beberapa
kendala, meliputi problem konseptual hukum jinayah, prinsip umum pembuktian,
dan prosedur pidana. Selain itu, Indonesia memiliki aturan tersendiri dalam
menerapkan hukum kirminal
seseorang sesuai dengan undang-undang kriminal yang berlaku yang sebagian besar
berbeda dengan aturan Islam. Penerapan hukum Islam di Indonesia yang menyeluruh
hanya menjadi slogan yang cukup mendapat simpati masyarakat/kalangan tertentu.
Kajian tentang hukum pidana secara sistematik dan strategis masih stagnan.
Penerapan hukum pidana Islam menurut pandangan
Gus Dur dituangkan dalam beberapa tulisan, seperti “Islam dan Hak Asasi
Manusia” dan “Hukum Pidana Islam dan Hak Asasi Manusia” yang membicarakan atau
memberikan perhatian pada masalah penerapan hukum pidana Islam dan hak asasi
manusia dan perubahan ketetentuan hukum yang bersifat ijtihadi sebagaimana
hukum pindah agama.
C. Problematika Fikih Jinayah
Hukum pidana/jinayah dalam
penerapannya berdampak pada hilangnya nyawa atau badan dan
pembatasan-pembatasan atas hak dan kebebasan seseorang. Dengan demikian, dalam
penerapannya membutuhkan terpenuhinya sejumlah prasyarat dan asas yang
diharapkan tidak berdampak pada terganggunya hak-hak asasi terpidana. Terdapat
beberapa prinsip penerapan hukum pidana menurut Gus Dur, yaitu sebagai berikut.
1.Pentingnya Mempertimbangkan Kemuliaan Manusia
dalam Hukum Jinayah
Ketentuan
penerapan hukum pidana harus memperhatikan status manusia dalam hukum Islam.[4]
Penerapannya harus tetap pada upaya mewujudkan kemaslahatan umum. Oleh karena
itu, tetkala menemukan sebuah kebuntuan dalam penerapan hukum pidana,
memungkinkan untuk mengambil bentuk-bentuk hukuman lain yang bertujuan
menciptakan kemaslahatan umat. Gus Dur mengatakan bahwa dimana ada penegakan
hukum, yang salah dihukum, maka ia telah memenuhi kewajiban syariah, yaitu
hukum Islam walaupun dalam penerapannya tidak menggunakan aturan yang telah
ditentukan oleh ajaran Islam.
Hukum
Jjinayah di satu sisi harus mampu memberikan efek jera terhadap pelaku
kriminal, akan tetapi di sisi lain harus mampu menjaga hak asasi manusia.
Sehingga literatur Islam yang ada dirumuskan sebagai respon kondisi sosial dan
politik yang dihadapi. Oleh karena itu, perlu adanya kajian mendalam tentang
penerapan hukum pidana Islam yang tetap menjaga hak asasi manusia sebagai
respon dari masyarakat Islam yang terus berkembang dan berubah-berubah.
Muhammad Alim menyebutkan
ada lima asas hukum pidana Islam, yaitu: 1). Asas legalitas; 2). Asas tanggung
jawab individu; 3). Asas tiada pidana dalam keterpaksaan; 4). Asas tiada pidana
dalam pembelaan diri; dan 5). Tiada pidana tanpa kesalahan.[5] Semua
asas ini perlu diperhatikan sebelum menerapkan hukum pidana yang diharapkan
dalam terjalin hubungan antara hukum pidana Islam dan hak asasi manusia.
2.Merumuskan Hubungan Hak Asasi dengan Hukum Pidana
Islam
Gus
Dur merumuskan beberapa aspek dalam menghubungkan antara hak asasi manusia dan
hukum pidana, yaitu pertama berkaitan dengan hukum acara, meliputi pengaduan,
pembuktian, dan jalannya proses pengadilan. Tuntutan haru didasarkan pada
kesaksian yang cukup dan memenuhi kriteria sebagai saksi. Sementara itu,
tertuduh berhak atas status tidak bersalah, sehingga ada bukti yang meyakinkan.
Kedua,
persyaratan administrasi yang menjamin terlaksananya pengadilan secara bersih,
jujur, dan berdasarkan pada keadilan. Persyaratan ini dilandaskan pada tidak
ada campur tangan dari pemerintah. Selain itu, jaminan akan tersedeianya hakim
yang memiliki kapasitas memadai, baik dari segi keahlian maupun kepribadian.
Ketiga,
pemberian keputusan dalam perkara pidana hukum Islam didasarkan atas dua
pendekatan yang saling melengkapi, yaitu menjunjung tinggi asas keadilan hukum
dan pemberian kesempatan seluas-luasnya untuk memperoleh keringanan hukum.
Hukuman maksimal yang menyangkut hukuman mati dan hukuman badan tidak dapat
dijatuhkan selama belum didapatkan bukti-bukti kesalahan yang cukup meyakinkan.
Hal tersebut sejalan dengan kaidah fikih “Al-hudud tasqutu bis syubuhat”. Hakim
harus meperhatikan kondisi terpidana apakah memungkinkan untuk menerima hukuman
ataukah tidak.
Keempat,
masih terbukanya kasus mengelak secara hukum, seperti kasus yang memungkinkan
penggantian hukuman dengan kompensasi material kepada pihak yang dirugikan
(Diyah). Di samping itu, sistem pengampunan menjadi bagian inheren dari hukum
pidana Islam, yang dikenal dengan nama sistem al-ifa.[6]
Uraian tersebut menunjukan
beberpa hal penting yang menyangkut pembuktian, persyaratan, dan
dimungkinkannya pergantian hukuman. Banyaknya persyaratn yang harus terpenuhi
berdampak pada sulitnya pelaksanaan hukuman pidana.
D. Contoh Kasus: Penerapan Hukum Riddah
Kata
riddah dapat dirujuk pada Al-Quran surah Al-Baqarah: 217 dan Al-Maidah:
54. Al-Baqarah: 217 secara umum menjelaskan bahwa orang yang kembali
meninggalkan agamanya adalah kafir, sementara Al-Maidah: 54 mengungkapkan
dengan bahasa yang hampir sama. Dua ayat tersebut tidak dengan tegas menentukan
hukuman had bagi yang murtad. Ketidakjelasan keterkaitan antara riddah
dan hukuman mati juga bisa dilihat dari beberapa ayat yang menjelaskan definisi
riddah dengan “Al-Kufru ba’dal iman” seperti surat Al-Imran: 86
dan 90 dan An-Nahl: 106.
Ketentuan
hukuman mati bagi pelaku riddah sesuai dengan dua hadis Nabi. Pertama,
hadist diriwayatkan dari Ibn Abbas yang artinya “Barang siapa mengganti
agamanya, maka bunuhlah”.[7]
Kedua, hadist yang artinya “Tidak halal darah seorang muslim
kecuali sebab salah satu dari tiga hal, yaitu laki-laki yang kafir setelah
Islamnya, berzina setelah pernikahannya, atau membunuh jiwa bukan karena jiwa”.[8]
Sebagaimana
dikemukakan Ibn Rusyd mengenai hadist tersebut, para ahli fikih sependapat
bahwa pelaku murtad laki-laki dihukum mati, walaupun bagi perempuan para uama
berselisih.[9]
Ketentuan hukum murtad tersebut juga terdapat pada kitab-kitab fikih yang masih
berlaku dan menjadi rujukan NU.
Masalahnya
adalah hukum riddah ini berbenturan dengan Deklarasi Universal HAM
(DUHAM) yang menyatakan bahwa berpindah agama adalah hak. Hal ini tercantum
pada pasal 18 yang berbunyi:
“Setiap orang bebas atas kebebasan pikiran,
hati nurani, dan agama. Dalam hal ini termasuk kebebasan berpindah agama atau
kepercayaan, dan kebebasan untuk menyatakan agama dan kepercayaan dengan cara
mengajarkannya, melakukannya, beribadah, dan mentaatinya, baik sendiri maupun
bersama-sama dengan orang lain, di muka umum ataupun sendiri”
Pemikiran
Gus Dur terkait kasus riddah dan hak berpindah agama dipaparkan dalam
tulisannya yang mengatakan bahwa masalah yang dihadapi umat Islam dalam
menerapkan hukuman mati bagi riddah jika diterapkan secara apa adanya
dalam realitas hidup sekarang menimbulkan sejumlah masalah, terutama
negara-negara Islam yang telah melakukan ratifikasi. Oleh karena itu,
menurutnya terdapat tuntutan untuk melakukan kajian kembali ketentuan fikih
yang secara formal sudah berabad-abad diikuti. Konsekuansi ini diambil karena
tidak mungkin bagi Indonesia untuk menolak begitu saja deklarasi DUHAM
tersebut.[10]
Dilematis
tersebut nyata-nyata dihadapi bangsa Indonesia yang mayoritas muslim.
Menurutnya kalau ketentuan tersebut diterapkan di Indonesia, maka lebih dari
dua juta jiwa orang yang berpindah agama dari Islam ke Kristen sejak tahun 1965
harus dihukum mati. Jika hal tersebut dilakukan, maka akan menimbulkan
permasalahan yang tidak kecil serta sulit dipecahkan. Dengan keadaan seperti
ini, Muslim Indonesia dihadapkan pada dua pilihan: 1). Menolak DUHAM atau; 2).
Mengubah diktum fikih itu sendiri.
Gus
Dur mengambil pilihan kedua, yaitu melakukan kajian kembali diktum fikih.
Konsekuensinya harus ditemukan mekanisme untuk mengubah ketentuan fikih yang
secara formal sudah berabad-abad diikuti dengan tetap berpijak pada kebesaran
Islam yang menetapkan keyakinan kepada Allah dan RasulNya serta beberapa ayat
muhkamat sebagai sesuatu yang harus dipegang. Lebih jelasnya, terdapat peluang
untuk melakukan kajian kembali terhadap ketentuan-ketentuan hukum yang bersifat
ijtihadi.
Apa yang dikemukakan oel Gus Dur memiliki kesamaan
dengan pandangan sejumlah pemikir Islam, seperti Ibrahim Moosa dan
pemikir-pemikir progresif yang lain.[11] Mereka
berpendapat bahwa murtad bukan berarti perlawanan terhadap agama yang harus
dikenai sanksi, karena semangat Al-Quran memberikan kebebasan kepada seseorang
untuk memilih keyakinan.[12] Asmawi
menambahkan bahwa Nabi sendiri semasa hidupnya belum pernah melaksanakan
hukuman mati bagi orang yang murtad.[13]
[1]
Ahmad Wardi Muslich, Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah,
( Jakarta: Sinar Grafika, 2004, ) h. 1
[2]
Dede Rosyada, Hukum Islam Dan Pranata Sosial, (Jakarta: PT. Raja
Grapindo Persada, 1994), h. 85-85
[3]
Johari, Fikih Gus Dur, (Jombang: Pustaka Tebuireng, 2019), h. 170.
[4] Abdurrahman Wahid, “Hukum Pidana Islam dan Hak Asasi Manusia”, dalam Islam
Kosmopolitan..., hal. 366.
[5] Muhammad Alim, Asas-asas Negara Hukum Modern dalam Islam, (Yogyakarta:
LKiS, 2010), hal. 341-356.
[6] Abdurrahman Wahid, “Hukum Pidana Islam dan Hak Asasi Manusia”, dalam Islam
Kosmopolitan..., hal. 373.
[7] Al-Imam An-Nasa’i, Sunan An-Nasa’i, (Beirut: Dar Al-Fikr, 1930), Juz
VII, hal. 104.
[8] Ibid.
[9] Ibn Rusyd, Bidayah Al-Mujtahid wa Nihayah Al-Muqtasid, (Indonesia:
Dar Ihya Al-Kutub Al-Arabiyyah, t.t.), hal. 343-344.
[10] Abdurrahman Wahid, “Hukum Pidana Islam dan Hak Asasi Manusia”, dalam Islam
Kosmopolitan..., hal. 122.
[11] Ibrahim Moosa, Islam Progresif: Refleksi Dilematis Tentang Hak Asasi
Manusia, Modernitas, dan Hak-Hak Perempuan dalam Islam, (Jakarta: ICIP,
2004), hal. 38.
[12] Ibid, 40-42.
[13] Muhammad Said Al-Asmawi, Penerapan Syari’at Islam dalam Undang-Undang
Belajar dari Pengalaman Mesir ..., hal. 140-142.
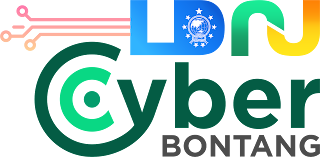


Posting Komentar